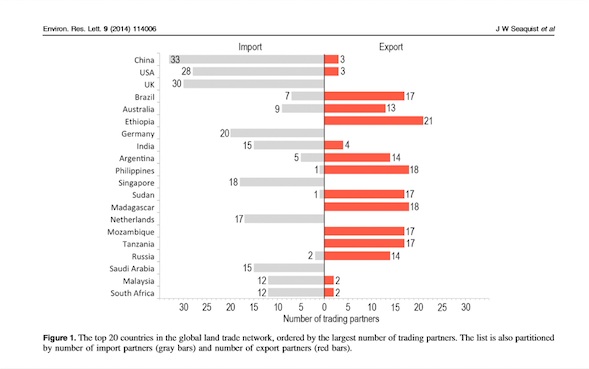22 February 2016 | Andre Barahamin
Ilustrasi gambar diambil dari wordpress.clarku.edu
TAHUN 2015 lalu, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
mencatat ada 5 orang yang tewas, 39 orang menjadi korban penembakan, 124 orang
dianiaya dan 278 orang lain ditahan.[1] Semua jumlah tersebut terkait dengan
konflik agraria di Indonesia yang semakin menunjukkan gejala peningkatan.
Setahun kemarin juga mencatat peningkatan jumlah kasus sengketa tanah sejak
lima tahun terakhir.
Selanjutnya, laporan KPA tersebut menyebutkan bahwa
pelaku kekerasan dalam berbagai konflik agraria di Indonesia, didominasi oleh
perusahaan (35 kasus), polisi (21 kasus) dan TNI (16 kasus). Dari total tersebut,
30 persen kasus terjadi di dua daerah, yaitu Riau (14,40 persen ) dan Jawa
Timur (13,60 persen). Sementara daerah lain seperti Sumatera Selatan (13,60
persen) dan Sulawesi Tenggara (6,40 persen) juga menjadi titik panas konflik
agraria.
Dari jumlah kasus agraria di atas, 50 persen merupakan
konflik di bidang perkebunan. Sisanya, 28 persen terjadi di konflik terkait
pembangunan infrastruktur (28 persen) dan sektor kehutanan (9 persen). Konflik
lain juga terjadi di sektor pertambangan dan pesisir.
Apa sebenarnya yang sedang terjadi?
Krisis Ekonomi
2008 dan Perubahan Tren Pasar Global
Sejak krisis finansial 2008 mereda, kita menyaksikan
fenomena global baru yang disebut dengan perampasan tanah secara luar biasa (massive
land grabbing). Yaitu sebuah model pengambilalihan kepemilikan tanah di
negara-negara miskin atau negara berkembang oleh perusahaan-perusahaan
multinasional. The Economist dalam laporannya di tahun 2009 mencatat
bahwa total ada sekitar 37-49 juta hektar yang telah berhasil dirampok sejak tahun
2006.[2] Jumlah ini diprediksi akan terus
meningkat di tahun-tahun berikutnya paska krisis 2008.
Sebuah laporan di awal November 2014 dari Lund
University, Swedia, membenarkan prediksi di atas.[3] Laporan tersebut memberikan gambaran
mengerikan tentang ekpansi perampasan tanah. Dari total 195 negara yang diakui
PBB, 126 di antaranya terlibat transaksi perdagangan tanah di mana Cina
(bertransaksi dengan 33 negara), Inggris (30 negara) dan AS (28 negara) muncul
sebagai pemain utama yang rajin membeli tanah dengan negara-negara di Afrika
dan Asia sebagai destinasi. Negara-negara seperti Ethiopia sebagai contoh,
telah menggadaikan tanahnya kepada 21 negara. Filipina dan Madagascar telah
membuka dirinya untuk 18 negara berbeda. Sementara Brazil, Sudan, Mozambique
dan Tanzania laris manis menjual tanah kepada investor dari 17 negara berbeda.
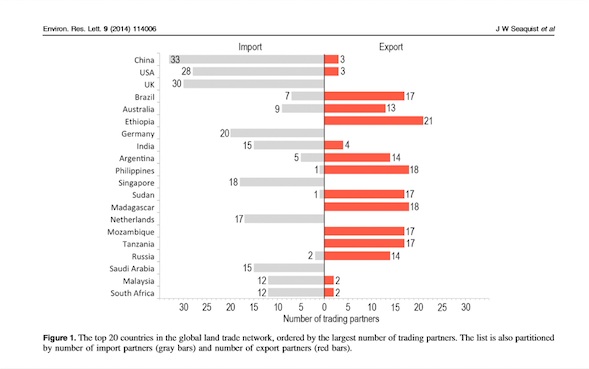
Model transaksi macam inilah yang disebut sebagai
“perdagangan virtual baru” yang mana membuat sebuah perusahaan dapat mengimpor
hal yang seharusnya tidak diperdagangkan. Berbeda dengan bentuk perdagangan
virtual lama yang hanya mendefinisikan proses transaksi jual beli di bursa
saham, perdagangan bentuk baru ini mengambil langkah maju yang lebih radikal.
Hari ini produk-produk seperti sumber air, tanah hingga polusi diperjualbelikan
melewati batas-batas negara.
Dalam kacamata ekonomi neoliberal, perdagangan virtual
memiliki beberapa keunggulan.
Misalnya, negara-negara yang memiliki empat musim dan
tanahnya tidak memungkinkan untuk ditanami buah-buahan tropis, dapat membeli
tanah di negara-negara tropis untuk kemudian diubah menjadi perkebunan skala
besar yang bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, tapi juga dapat
memenuhi ambisi ekspor ke negara lain. Cara lain yang dapat ditempuh adalah
dengan mengubah negara-negara yang masih memiliki lahan yang cukup menjadi
lumbung pangan dunia, seperti yang sedang terjadi di Merauke, Papua, melalui
program sejuta hektar sawah baru yang terintegrasi dalam skema Merauke
Integrated Food and Energy Estate (MIFEE).[4] Sebagai gantinya, negara-negara yang
telah merelakan tanah mereka kemudian diberikan kemudahan dalam skema pengajuan
hutang dan garansi keterlibatan yang lebih luas dalam kancah politik luar
negeri berbentuk aliansi-aliansi regional atau internasional.
Jenis perdagangan virtual seperti ini juga memiliki
tujuan untuk mencegah monopoli sebuah negara terhadap kekayaan sumber daya alam
yang mereka miliki. Monopoli oleh negara dipandang buruk karena tidak sejalan
dengan skema liberalisme total di mana pasar akan diberikan kekuasaan
sepenuhnya dan korporasi adalah pengendali utamanya. Jenis ‘perdagangan virtual
baru’ membuat negara-negara kaya mampu memiliki akses legal untuk melakukan
penggerukan sumber daya alam yang dimiliki negara-negara miskin atau
negara-negara berkembang untuk meningkatkan kapasitas konsumsi domestiknya.
Sebagai contoh kita dapat melihat soal ekstraksi mineral
Cobalt (Co) yang menjadi salah satu bahan baku untuk baterai ponsel pintar
(smartphone). Material ini paling banyak terdapat di Kongo yang menjadi pemasok
40 persen kebutuhan pasar global,[5] selain juga cadangan di Zambia dan
Republik Afrika Tengah. Di Kongo sendiri, ekstraksi Cobalt dijalankan oleh
Central African Mining and Extraction Company (CAMEC), yang berkantor pusat di
London, Inggris. CAMEC sendiri terkenal sebagai pelaku perdagangan kotor (Blood
Cobalt) dan perbudakan anak-anak di bawah umur.[6]
Pasar Pangan dan
Energi
Merebaknya jenis perdagangan baru ini, juga disebabkan
oleh meningkatnya harga minyak bumi dan batu bara dalam beberapa tahun
terakhir: biaya produksi yang dianggap semakin mahal sementara cadangan sumber
daya yang semakin menipis. Oleh karenanya, tuntutan untuk menemukan
sumber-sumber energi baru semakin menguat. Ini adalah salah satu poin pendorong
lahirnya tren ‘energi alternatif’ yang mulai ramai sejak awal 2009 kemarin. Isu
pemanasan global sejak satu dekade lalu telah direkuperasi sekaligus menjadi
momentum yang tepat untuk ekonomi neoliberalisme bergerak merevitalisasi
dirinya setelah dihantam krisis. Ditambah lagi dengan meningkatnya laju
populasi di seluruh dunia, sehingga isu mengenai kebutuhan akan ketersediaan pangan
menjadi hal mutlak yang tidak bisa diacuhkan.
Meski penting untuk dipahami bahwa perampasan tanah
bukanlah fenomena yang baru terjadi belakangan ini. Brutalitas yang sama telah
terjadi sejak beratus-ratus tahun lalu. Contohnya adalah kedatangan para kolonial
Eropa untuk mencari dunia baru yang akhirnya membuka jalan terhadap perampasan
tanah dan penyingkiran masyarakat asli. Contoh-contoh kasusnya membentang dari
pedalaman Amazon, gurun Sahara hingga apa yang sedang berlangsung di Papua saat
ini. Proses kekerasan yang secara esensi dan formasi serupa dan masih terus
terjadi. Jauh sebelum tren global berubah, di Indonesia kita menyaksikan
bagaimana isu konservasi lingkungan justru berbalik digunakan sebagai alasan
bagi negara dan perusahaan untuk mengusir masyarakat asli dari tanah ulayat
mereka.
Kasus kawasan konservasi Kerinci yang mengusir Orang
Rimba, penyingkiran masyarakat dari dalam Hutan Lindung Lore Lindu, hingga
Malind-Anim yang harus merelakan tanah ulayat untuk pembangunan Hutan Lindung
Wasior, adalah beberapa contoh di antaranya.
Namun hari ini, sesuatu yang lebih brutal sedang
berlangsung. Dua krisis global yang terjadi dalam kurun waktu kurang dari dua
tahun (yaitu krisis finansial 2008 dan krisis pangan di periode 2007-2008)[7] telah berhasil membuka penemuan
jalan baru bagi neoliberalisme. Dua agenda yang awalnya tampak berjalan paralel
kini telah menemukan titik temu dan berjalan bergandeng tangan.
Pertama adalah masalah ketahanan pangan. Banyak
negara maju yang selama ini menggantungkan dirinya pada impor pangan dan selalu
khawatir mengenai pengetatan pasar, akhirnya menemukan saluran baru untuk
menginvestasikan keberlimpahan uang dari dalam negerinya. Investasi yang
dipandang jauh lebih aman dan memberi garansi keuntungan jangka panjang dan
konsisten berbentuk sistem ‘outsourcing’ dalam produksi pangan. Caranya adalah
dengan membeli kontrol terhadap produksi sumber-sumber makanan di negara-negara
miskin dan negara-negara berkembang melalui perusahaan-perusahaan
multi-nasional. Kekhawatiran akan ketidakmampuan sebuah negara yang maju dalam
ekonomi dan teknologi untuk menyediakan pangan berkualitas dan terjangkau bagi
penduduk negaranya, berhasil dijawab melalui model ‘perdagangan virtual’ yang
murah.
Pemerintah di negara-negara yang menjadi sasaran tembak,
ditawarkan untuk mendapatkan sejumlah kecil keuntungan dari pasar pangan berupa
kucuran dana segar untuk pembangunan infrastruktur dan sokongan untuk pembangunan
bisnis properti yang telah terbukti dahulu gagal dan memicu krisis ekonomi
global. Alasan ini mendorong Cina, US dan Inggris begitu aktif mencari
‘tanah-tanah baru’ di Afrika dan Asia sebagai cadangan pangan. Agar tampak
lebih humanis, negara-negara koloni itu disebut sebagai ‘lumbung pangan dunia’.
Ilusi yang sebenarnya digunakan untuk menutupi liberalisasi pangan guna
kepentingan daya tahan sekaligus perluasan pasar.
Ini adalah strategi jangka panjang yang cerdas karena
berhasil menjawab dua kebutuhan dalam satu sapuan. Pertama, untuk menepis
keraguan mengenai krisis pangan (persoalan cadangan dan akses harga) di masa
depan yang mungkin terjadi di negara-negara maju, sekaligus memberikan
keuntungan karena tersedianya jumlah konsumen yang terus membesar dan jumlah
permintaan yang terus meningkat.
Sebagai contoh, sejak Maret 2008 pemerintah Arab Saudi,
Jepang, China, India, Korea, Libya dan Mesir telah mengutus para pejabat
tingginya untuk bernegosiasi dan mencari lahan pertanian subur di berbagai
tempat seperti Uganda, Brasil, Kamboja, Sudan, Pakistan, India, Indonesia dan
Filipina. Proses ini dilakukan melalui sebuah praktik diplomatik bilateral
maupun regional. Ironisnya negara-negara yang menjadi sasaran kerjasama
tersebut justru termasuk rentan dan sedang mengalami krisis pangan domestik. Di
Darfur, Sudan, misalnya terdapat sekitar 5,6 juta pengungsi yang membutuhkan
makanan.[8] Di Kamboja, sekitar 100 ribu unit
keluarga mengalami kekurangan pangan.[9] Di Indonesia sendiri, harga beras
terus menerus melambung sejak tahun 2008 bersamaan dengan kemiskinan yang
semakin meluas hingga membuat akses terhadap pangan bertambah sulit. Ironisnya
untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah di negara-negara tersebut justru
mengandalkan impor secara berkala dan masif. Di saat yang bersamaan membuka
dirinya untuk praktek jual-beli lahan untuk industri berskala besar di bidang
pertanian.
Jalur kedua adalah keuntungan finansial.
Mengingat krisis keuangan saat ini, segala macam pemain di industri keuangan
dan pangan – melalui rumah investasi yang mengelola dana pensiun pekerja, dana
ekuitas swasta – telah bergerak aktif mencari formulasi-formulasi baru yang
dapat memberikan keuntungan secara cepat, konsisten dan terus membesar.
Dana-dana jaminan secara berkala dalam jumlah besar terus dialihkan dari pasar
derivatif yang sekarang runtuh. Pedagang gabah mencari strategi baru dengan
beralih ke tanah, sebagai sumber untuk makanan dan bahan bakar produksi
Tanah itu sendiri awalnya bukanlah investasi yang
familiar untuk banyak perusahaan-perusahaan transnasional. Sebabnya, tanah
dipandang sarat dengan konflik politik di mana, dalam banyak kasus, selalu
mengalami problem mengenai kepemilikan dan beberapa peraturan pembatasan yang
mengatur soal pelarangan pihak asing untuk tidak dapat membeli lahan.
Mengalihkan model dagang dengan menyasar tanah juga bukan pekerjaan yang murah
dan singkat. Untuk mendapatkan keuntungan, investor harus meningkatkan
kapasitas produksi tanah yang tentu saja memakan waktu dan biaya. Hal ini juga
berarti beban kerja yang lebih berat jika dibandingkan dengan bisnis finansial
atau tambang mineral. Tapi krisis gabungan antara kelangkaan sumber makanan dan
problem di sektor keuangan telah mengubah nilai lahan pertanian di mata
investasi. Fakta lain yang mendukung adalah murahnya harga tanah di
negara-negara miskin dan negara berkembang. Kondisi yang turut dipengaruhi oleh
pelemahan nilai tukar mata uang dan ketergantungan ekonomi negara-negara
selatan yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Negara-negara maju yang telah sejak lama menyerahkan
kendali pengelolaan kepentingan publik kepada korporasi dengan mudah memberikan
mandat bagi badan-badan multinasional ini untuk ikut terlibat. Sebab lainnya
adalah ketidakberdayaan negara pasca krisis finansial yang membuat banyak
pemerintahan tidak memiliki dana yang cukup untuk melakukan invetasi baru
berbiaya tinggi. Oleh karenanya, menyerahkan kerja-kerja tersebut kepada
perusahaan transnasional menjadi opsi yang paling masuk akal.
Itu mengapa, Anda tidak perlu kaget jika melihat ke
sekeliling dan menemukan bahwa produksi pangan yang dilakukan oleh
perusahaan-perusahaan multinasional ini sama sekali tidak ditujukan untuk
menjawab kebutuhan pangan masyarakat sekitar. Infografis di atas, yang
menggambarkan jumlah transaksi tanah di berbagai negara, mesti dipahami sebagai
bagaimana ekspansi perusahaan multinasional yang terkadang mengatasi isu-isu
kepentingan domestik sebuah negara. Namun, tentu ada perbedaan mendasar yang
penting digarisbawahi dari ragam investasi sektor pangan yang dimotori
negara-negara maju.
Cina, misalnya, meski memiliki wilayah yang cukup luas,
namun jumlah populasi yang tidak berhasil dikontrol membuat ketersediaan pangan
adalah isu serius di negeri ini. Ditambah lagi dengan berkurangnya secara drastis
luas lahan pertanian produktif yang berlangsung sejak dua dekade terakhir.
Penyusutan tersebut tidak lepas dari masifnya industrialisasi. Ketimpangan itu
jelas terlihat. Jumlah petani di Cina berkisar 40 persen dari total petani di
dunia, namun lahan yang tersedia hanya 9 persen dari keseluruhan luas lahan
produktif di dunia. Karenanya tidak mengejutkan jika Partai Komunis Cina
menjadikan persoalan pangan dan energi sebagai prioritas. Dengan cadangan
devisa yang mencapai 1,8 trilyun dolar, Cina memiliki kelimpahan finansial
untuk digunakan dalam investasi.
Para pemimpin serikat tani di negara-negara Asia Tenggara
telah mengetahui dengan jelas bahwa Negeri Tirai Bambu telah memulai
‘outsourcing pangan’ sejak awal 2007, jauh sebelum krisis terjadi.[10] Dengan politik luar negeri yang
agresif, Cina berhasil memaksakan lebih dari 30 perjanjian investasi di bidang
pertanian di kawasan Asia Tenggara. Sebagai gantinya, Beijing menyediakan
teknologi, pelatihan dan kucuran uang untuk pembangunan infrastruktur
pendukung, seperti dam-dam raksasa dan jalur transportasi yang nantinya akan
mendukung mata rantai distribusi. Pelebaran sayap ini juga bahkan sampai ke
Asia Selatan dan Afrika. Hasilnya, sekitar 12 negara telah resmi dijadikan
mitra kerjasama dalam pengembangan mega-bisnis di bidang agrikultur.
Secara umum dapat dikatakan bahwa model perampasan tanah
oleh Cina tergolong yang paling konservatif. Selain mengacuhkan
‘pedoman-pedoman etis’ dalam investasi, Cina sangat protektif terhadap
investasinya dan di saat bersamaan berupaya dengan segala cara memaksimalkan
segala peluang yang dapat menggaransikan pasokan pangan berkelanjutan untuk negara
itu di masa depan. Hal ini tidak lepas dari kenyataan bahwa di dalam negeri,
Cina mengalami kekurangan lahan pertanian dan sumber air yang dapat dipasok
untuk menghidupi lahan-lahan agar produktif. Negeri ini ‘tidak memiliki pilihan
lain’ selain menggalakkan investasi pangan di luar negeri.[11]
Selain Cina, ekspansi gila-gilaan juga dilakukan oleh
negara-negara Teluk seperti Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi dan Uni
Emirat Arab. Meski patut dipahami bahwa negara-negara di kawasan Teluk ini
menghadapi realitas yang sama sekali berbeda dengan Cina. Dibangun di padang
gurun, negara-negara ini memiliki persoalan kelangkaan tanah dan air sebagai
prasyarat untuk melakukan produksi pertanian. Tapi sejumlah besar kekayaan yang
didapatkan dari minyak memberikan kekuatan untuk membayar ketergantungan mereka
terhadap negara-negara penghasil pangan. Namun strategi ini bukan tanpa masalah.
Ketika krisis pangan terjadi, ketergantungan terhadap nilai tukar mata uang
terhadap dolar yang ikut dipengaruhi oleh krisis finansial membuat
negara-negara ini kemudian mesti menanggung beban inflasi yang membengkak.[12] Apalagi ketika terjadi krisis 2008,
para pekerja migran berupah rendah yang merupakan populasi mayoritas di
negara-negara ini mengalami kesulitan untuk mengakses pangan sehingga
mengharuskan subsidi dari negara untuk menyediakan makanan dengan harga
terjangkau demi mencegah kerusuhan sosial.[13] Selain fakta bahwa industri
penyewaan dan jual beli properti di kawasan ini juga ikut terpukul dengan
kolapsnya ekonomi global. Ini adalah dorongan-dorongan utama yang menjadi
alasan bagi negara-negara di kawasan Teluk untuk mengambil jalan lain dan
mengalihkan investasi ke sektor pangan.
Melalui Gulf Cooperation Council (GCC) yang menjadi badan
kerjasama negara-negara di kawasan Teluk, mereka kemudian merumuskan strategi
bersama ‘outsourcing pangan’ di negara-negara produsen beras seperti Asia
Selatan dan Asia Tenggara. Ide utamanya adalah melakukan penawaran (khususnya
kepada negara-negara di mana Muslim adalah mayoritas, seperti Indonesia dan
Malaysia) untuk memberikan pinjaman berbunga rendah, minyak dengan ‘harga
khusus’ sebagai alat tukar untuk mendapatkan akses ke lahan-lahan pertanian.
GCC menawarkan pembukaan anak perusahaan di negeri-negeri seperti Burma,
Kamboja, Indonesia, Laos, Filipina, Vietnam, dan Pakistan yang secara spesifik
menjadi kontraktor ekspor pangan ke negara-negara di kawasan tersebut.
Strategi ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Buktinya,
antara Maret hingga Agustus 2008, negara-negara GCC melalui konsorsium atau
perusahaan tunggal telah berhasil mengamankan sewa terhadap jutaan hektar lahan
pertanian yang memulai panen di pertengahan tahun 2009. Setelah sebelumnya di
Januari 2009, GCC melakukan pertemuan yang didedikasikan untuk merumuskan
poin-poin kritis terkait kerjasama regional ini sebelum kemudian disepakati
sebagai kebijakan bersama yang resmi.[14]
Pemain lain dalam zona investasi ini adalah Jepang dan
Korea Selatan. Pemerintah dua negara kaya dari Asia Timur ini bahkan sejak lama
telah sepenuhnya bersandar kepada impor untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam
negeri masing-masing. Kebutuhan pangan dalam negeri Jepang sebesar 60 persen
merupakan impor. Sementara Korea, sekitar 90 persen beras dari keseluruhan
konsumsi domestik ditebus dari negara lain.
Di permulaan tahun 2008, pemerintah Korea Selatan
mengumumkan bahwa mereka telah merumuskan sebuah rencana nasional untuk
memfasilitasi akuisisi lahan di luar negeri dalam rangka memenuhi kebutuhan
produksi makanan Korea. Rencana ini tentu saja akan diserahkan kepada pihak
swasta sebagai pemain utama. Langkah awalnya adalah dengan membeli tanah di
Mongolia dan Rusia Timur, untuk memproduksi makanan yang akan diekspor kembali
ke Korea Selatan. Di saat yang bersamaan penjajakan kerjasama serupa juga
tengah menyasar Sudan, Argentina dan Asia Tenggara.
Jepang, di sisi lain tampaknya bergantung sepenuhnya
kepada sektor swasta untuk mengatur impor pangan. Sementara pemerintah bertugas
memberikan bingkai politik melalui perjanjian perdagangan bebas, perjanjian
investasi bilateral dan pakta kerja sama pembangunan. Ini adalah peran pasif
yang diemban negara. Itu sebabnya di dalam negeri, Jepang memiliki kebijakan
administratif yang menghalangi segala bentuk upaya untuk melakukan
restrukturisasi dan reformasi sektor pertanian dalam negeri. Di negeri ini ada
larangan yang tidak memperbolehkan keluarga atau perusahaan untuk memiliki
tanah yang akan digunakan untuk bisnis pertanian. Kepemilikan tanah luas yang
dipusatkan di tangan negara membuat penduduknya tidak memiliki pilihan lain
kecuali menggantungkan diri pada impor.
Di tempat lain, tren investasi ini juga ikut merambah
India. Sektor pertanian dalam negeri dianggap telah sangat berantakan dan
membutuhkan biaya yang besar untuk memperbaikinya. Berbanding terbalik dengan
tawaran yang jauh lebih murah dan lebih menjanjikan jika menggelontorkan dana
untuk mengambil alih lahan-lahan pertanian di negeri asing. Perlawanan terus
menerus dari serikat-serikat tani India dan gerilyawan pemberontak Naxalite
terkait perampasan tanah, membuat alasan di atas semakin masuk akal. Upaya
untuk meliberalisasikan tanah dalam kawasan-kawasan ekonomi khusus menghadapi
masalah serius terutama di bidang keamanan. Belum lagi menyoal persoalan
kelangkaan air dalam jangka panjang untuk mendukung industri pertanian.
Ditambah dengan kekhawatiran soal bakal tertinggalnya India dalam percaturan
bisnis pangan membuat banyak perusahaan negara kemudian mengalihkan sasaran
untuk menghasilkan produk makanan di luar negeri. Jenis yang diincar adalah
tanaman biji berminyak (oilseed crops), kacang-kacangan dan kapas. Strategi
ini, misalnya, berjalan sukses di Burma yang di akhir 2009, berhasil memasok 1
juta ton dari total kebutuhan impor kacang-kacangan yang mencapai angka 4 juta
ton per tahun untuk menutupi kekurangan produksi dalam negeri yang hanya
mencapai 15 juta ton dari kebutuhan konsumsi domestik yang mencapai hampir 20
juta ton per tahun. Dengan dukungan aktif pemerintah, perusahaan-perusahaan
asal India berhasil mendapatkan ijin pengelolaan lahan di Burma, dengan harga
sewa dan upah buruh yang lebih murah ketimbang melakukan produksi di dalam
negeri. Junta militer di Burma begitu kooperatif terhadap investasi asing. Hal
yang menjadi alasan di balik dukungan finansial pemerintah India untuk
pembangunan infrastruktur pelabuhan dan dorongan aktif untuk terlibat dalam
perdagangan bebas.
Selain Burma, India juga melebarkan sayapnya dengan
berinvestasi di Indonesia, Paraguay, Brazil dan Uruguay. Di Indonesia, India
melakukan investasi serius di sektor perkebunan kelapa sawit yang menjadi
sumber biofuel. Di Amerika Latin, target mereka adalah mencari tanah untuk
ditanami kacang-kacangan agar bisa memutus ketergantungan terhadap produksi
dalam negeri. Untuk mendukung itu semua, India melakukan deregulasi terkait
ijin bagi perusahaan-perusahaan multinasional dalam melakukan kerjasama lintas
negara, pembelian properti di luar negeri dan dukungan modal untuk investasi
skala raksasa di bidang pertanian.
Dukungan untuk perluasan perkebunan-perkebunan yang akan
menjadi sumber energi biofuel juga dilakukan oleh Inggris dan AS. Mensponsori
pembukaan ladang-ladang sawit dan perkebunan tebu skala raksasa menjadi tren
baru. Untuk itu, ekspansi kemudian diarahkan ke wilayah Asia Tenggara yang
hangat dan masih memiliki banyak lahan yang tersedia. Filipina, Malaysia dan,
tentu saja, Indonesia menjadi sasaran empuk. Inggris dan AS bahkan ikut
mendukung terbentuknya pakta perdagangan sawit regional antara Indonesia dan
Malaysia.[15] Pakta kerjasama ini diharapkan
dapat mengurangi kompetisi antar kedua negara penghasil sawit terbesar di dunia
untuk kemudian dapat saling membantu dalam ekstensifikasi industri minyak sawit
mentah (crude palm oil).
Industri biofuel dengan bahan baku sawit, jagung dan tebu
memang menjadi isu strategis lima tahun terakhir. Peralihan tendensi
negara-negara maju dan perusahaan-perusahaan trans-nasional untuk mulai secara
perlahan meninggalkan energi fosil yang tidak terbarukan menuju sumber energi
yang lebih murah bukan diakibatkan kepedulian akan krisis iklim atau ketakutan
soal degradasi lingkungan.
Biofuel dianggap sebagai solusi pasar yang lebih
rasional. Ia sama sekali telah mengacuhkan dan akan tetap tidak peduli dengan
seruan-seruan mengenai penyelamatan lingkungan yang dikampanyekan oleh aktivis
lingkungan. Argumentasi paling telanjang dapat ditemukan melalui Robert J.
Samuelson, yang mengatakan[16] bahwa peralihan tersebut sebenarnya
sangat sederhana. Bahwa industri tidak menyukai harga bahan bakar yang tinggi.
Mendapatkan sumber bahan bakar dengan harga yang lebih murah jelas menjadi
tawaran menggiurkan untuk menekan biaya produksi dan memperbesar keuntungan.
Untuk itu, berbagai pembenaran gila disodorkan kepada publik mengenai betapa
pentingnya peralihan dari energi fosil menuju biofuel. Bahwa semua orang akan
diuntungkan dari peralihan ini, mulai dari petani, kalangan konsumen dan tentu
saja para pelaku industri. Bahwa biofuel akan membuka lapangan pekerjaan di
desa-desa dan
membuat negara mampu menghemat anggaran yang biasanya
dibelanjakan untuk membeli minyak dari negara-negara asing.
Oleh sebab itu menjadi kewajaran, misalnya, jika dalam
pertemuan konferensi internasional mengenai perubahan iklim beberapa tahun
belakangan ini,[17] para pelaku industri dan pemegang
kebijakan begitu ramah terhadap tuntutan untuk mulai mengurangi penggunaan
energi tidak terbarukan yang bersumber dari batu bara dan minyak bumi. Mereka
tampak berada di satu jalur yang sama dengan para aktivis lingkungan dalam
upaya penyelamatan lingkungan dan pencegahan krisis iklim menjadi lebih buruk.
Meskipun jika dilihat secara radikal, tidak ada perubahan komitmen yang lebih
serius mengenai langkah-langkah praktis dan detil yang harus diambil untuk
mencegah degradasi lingkungan semakin parah.
Itulah alasan yang ikut mendorong perluasan besar yang
akhirnya menjadi industri perkebunan sawit sebagai emas baru di Asia Tenggara.
Kenyataan ini tidak lepas dari fakta bahwa sawit merupakan bahan baku paling
murah untuk biofuel jika dibanding dengan jagung dan kedelai. Bersamaan dengan
itu, konsumsi minyak sawit di dunia terus menunjukkan gejala peningkatan dari
tahun ke tahun.
Indonesia sendiri merupakan kekuatan paling besar di
sektor ini dengan luas lahan mencapai 15 juta hektar (per tahun 2014) yang
tersebar dari Sumatra, Kalimantan, Papua dan sebagian kecil di Sulawesi.
Malaysia berada di posisi kedua dengan luas lahan mencapai hampir 5 juta
hektar. Kedua negara ini menyuplai 85% kebutuhan sawit dunia.[18] Menyusul di belakangnya adalah
Thailand yang memiliki sekitar 650 ribu hektar sawit.
Mega-agribisnis tentu saja memiliki masalah serius.
Friends of the Earth mencatat bahwa 87 persen deforestasi yang berlangsung di
Malaysia sejak tahun 1987 hingga tahun 2000 disebabkan oleh pembukaan lahan
untuk perkebunan sawit skala besar. Di Indonesia, WALHI dan Green Peace telah
berkali-kali menyebutkan dalam berbagai laporan mereka sejak lima tahun
terakhir bahwa laju deras penebangan hutan tropis dan pengeringan lahan-lahan
gambut disebabkan sebagian besarnya oleh ekspansi industri kelapa sawit.
Indonesia dan Malaysia masing-masing tercatat memproduksi sekitar 25 juta dan
19 juta ton sawit mentah di tahun 2012. Thailand menyumbang kontribusi sebesar
2 juta di tahun yang sama.
Di Indonesia, dari luasan bentang lahan perkebunan sawit
tersebut, sebagian besarnya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan multinasional.
Riset yang dilakukan oleh TuK Indonesia[19] menemukan bahwa 62 persen lahan
sawit di Kalimantan dikuasai oleh lima perusahaan besar, yaitu Sinar Mas,
Salim, Jardine Matheson, Wilmar dan Surya Dumai. Perusahaan-perusahaan ini juga
dominan di Sumatra dengan penguasaan yang mencapai 32 persen dari total seluruh
perkebunan.

Peralihan bentuk energi ini sebenarnya telah terjadi jauh
sebelum kolapsnya ekonomi dunia di tahun 2008. Krisis finansial pada akhirnya
hanyalah memperkuat basis argumentasi mengapa migrasi energi menjadi mendesak
untuk dilakukan. Royal Dutch Shell misalnya, hingga tahun 2007 telah
mengucurkan dana lebih dari 1 milyar US dollar selama lima tahun ke belakang
untuk penelitian, pengembangan dan proyek-proyek percobaan biofuel, pembangkit
listrik tenaga matahari dan atau tenaga angin, dan hidrogen. Meski di tahun
yang sama, bersama Chevron, Shell menginvestasikan 10 milyar dolar US untuk
proyek pertambangan pasir di Kanada dan Afrika.
Perusahaan otomotif seperti Ford dan BMW, juga kemudian
mulai menganggarkan biaya riset untuk kemudian menciptakan mobil yang lebih
ramah lingkungan dan menggunakan energi biofuel atau sumber energi lain seperti
matahari sebagai bahan bakar. Ujicoba-ujicoba ini diharapkan akan membuka ruang
yang lebih luas untuk penemuan-penemuan dalam skala yang lebih luas dan tentu
saja masif. Targetnya adalah untuk mengalihkan tren penggunaan bahan bakar
fosil yang dianggap kotor dan merusak lingkungan menuju mode baru yang lebih
murah, tanpa harus mengorbankan diri dengan kehilangan pasar konsumen yang
telah terbentuk selama berdekade.
Bersamaan dengan itu, perusahaan-perusahaan yang kini
mengalihkan perhatiannya ke sektor perkebunan kemudian menganggarkan dana
pertanggungjawaban sosial (Corporate Social Responsibility/CSR) untuk mendukung
program-program pengalih perhatian. Aksi-aksi tanam pohon, bersih
lingkungan-alam dan sejenisnya yang disponsori oleh dana CSR tidak lain
merupakan bentuk investasi tidak langsung sekaligus untuk menyuap pemerintah
dan “pekerja sosial kerah putih” untuk mendukung atau minimal tidak mengganggu
jalannya investasi di sektor industri pangan dan energi.
Penjelasan di atas mungkin terdengar seperti sebuah
permainan raksana di mana hanya para presiden, perdana menteri dan CEO
perusahaan yang memiliki hak untuk bicara dan menentukan arah ke mana
masyarakat hari ini akan melangkah. Tapi faktanya, negara-negara Asia dan
Afrika menjadi target empuk perampasan tanah, sejak 2008 justru tampak begitu
sumringah menerima banyaknya proposal-proposal proyek yang disertai kucuran
dana hutang. Bagi pemerintah di Asia dan Afrika, investasi di sektor apapun
selalu wajib diterima hangat. Sebab ini berarti akan terbukanya kesempatan dan
sumber pembiayaan untuk melakukan modernisasi di daerah-daerah pedesaan (rural
areas), pembangunan infrastruktur yang semakin cepat, konsolidasi kegiatan industri
pertanian serta peluang untuk kemudian dilibatkan lebih sering dalam percaturan
politik luar negeri.
Menyewakan lahan-lahan produktif di negaranya untuk
kepentingan industri pangan dengan label menjadi “lumbung pangan nasional”
merupakan kehormatan bagi negara-negara di Asia dan Afrika. Yang menjadi paling
penting adalah bagaimana kemudian negara-negara maju akhirnya menunjukkan
ketergantungannya yang baru terhadap negeri-negeri miskin dan berkembang,
selain buruh murah dan industri pariwisata seperti dekade-dekade yang lampau.
Blok-blok perdagangan regional di Asia dan Afrika
didorong untuk terus membuka diri agar investasi sektor agribisnis dapat dengan
mudah melakukan penetrasi. Penandatanganan perjanjian dagang antara ASEAN
dengan negara-negara kayak seperti Australia, Selandia Baru, Cina dan Uni Eropa
sebagai contohnya. Di saat yang bersamaan, para pemimpin negara-negara ini
berlomba-lomba untuk mempromosikan dirinya sebagai tempat yang aman dan nyaman
untuk dunia investasi pangan dan energi.
Sayangnya, rincian yang detil mengenai berapa banyak
perampasan tanah ini telah dan akan berlangsung untuk kepentingan produksi
pangan di luar negeri – di mana lokasinya, berapa hektar yang akan dirampas,
siapa investornya, model pendanaan yang dilakukan, siapa mitra pengusaha lokal
yang diajak bekerja sama – tidak mudah didapat. Sangat jelas bahwa pemerintah
begitu ketakutan jika kemudahan akses akan data-data tersebut dapat memicu
kerusuhan sosial atau protes berkepanjangan.
Indonesia: Zona
Perang Tanah
Memandang kondisi di atas, kita perlu menengok warisan
penting dari Amartya Sen, mengenai bencana kelaparan sebagai sebuah produk dari
monopoli pangan. Pemenang Nobel Ekonomi asal India ini dahulu telah melakukan
kritik terhadap pendekatan Malthusian yang menyederhanakan masalah dengan
memandang bahwa bencana kelaparan timbul akibat berkurangnya ketersediaan
pangan.[20] Sen justru melihat bahwa bencana
kelaparan justru tidak disebabkan oleh macetnya mata rantai suplai pangan.
Sebaliknya, yang terjadi adalah runtuhnya kemampuan dan hak seseorang untuk
mengakses sumber pangan secara legal – termasuk di dalamnya adalah pemanfaatan
peluang produktif, kesempatan perdagangan, hak-hak kelayakan ketika berhadapan
dengan negara, dan metode lain yang biasanya digunakan seseorang untuk
mengakses pangan.[21] Untuk menjawab persoalan itu, Sen
mengajukan demokrasi sebagai sebuah cara yang dapat dimanfaatkan untuk
mengatasi persoalan ketimpangan distribusi dan akses akan makanan.
Namun persoalannya adalah instrumen demokrasi hari ini
justru semakin tampak tidak efektif untuk mencegah bencana kelaparan di sebuah
region yang justru mengalami keberlimpahan pangan.[22] Perangkat demokrasi, justru makin
efektif digunakan untuk perluasan monopoli dalam sektor industri pangan.
Demokrasi sebaliknya tampak begitu masuk akal dan logis untuk mengajukan upaya
liberalisasi penuh sektor pangan dan energi. Demokrasi dan sistem ekonomi
neoliberalisme kemudian mengorganisir dirinya ke dalam bentuk lembaga-lembaga
donor yang anggotanya adalah negara-negara maju pemberi hutang dan
negara-negara miskin atau negara berkembang yang akan menjadi target pasar.
Di Indonesia, sebagai contoh. Dalam “Buku Biru” BAPPENAS,[23] terdapat 29 kategori program yang
akan melibatkan dana hutang dalam proyek-proyeknya. Misalnya pembiayaan Dam
Jatigede di Jawa Barat yang akan menggunakan dana pinjaman sebesar 52.200.000
US dolar. Pembiayaan Program Pengembangan Air Minum (Drinking Water Development
Program), pemerintah akan menganggarkan pinjaman sebesar 1.197.680.000 US dolar
yang tidak termasuk suntikan uang swasta sebesar 59.434.000 US dolar. Sementara
untuk infrastuktur transportasi, semisal pembangunan jalan tol Manado-Bitung di
Sulawesi Utara, pemerintah akan menggunakan dana hutang sebesar 80.000.000 USD
ditambah dengan pembiayaan dari belanja kas negara sebesar 8.000.000 USD. Lalu
akan ada hutang sebesar 201.000.000 US dolar yang nanti dibelanjakan dalam
program yang disebut sebagai Rural Settlement Infrastructure Development
(RSID). Program ini akan juga menyedot kas pemerintah sebesar 10.050.000 US
dolar untuk kemudian memperbaiki jalan, membuka jalan baru, drainase dan
sanitasi di daerah-daerah pedesaan. Targetnya tentu saja adalah daerah-daerah
yang nanti akan termasuk dalam mata rantai distribusi pasar.
Daftar di atas bisa diurutkan lebih panjang lagi. Dokumen
setebal 246 halaman ini, memang secara rinci mengurutkan berapa banyak biaya
yang akan dibebankan dari hutang, kementerian mana saja yang akan bertanggung
jawab terhadap pelaksanaan proyek dan tentu saja menyebutkan lokasi proyek.
Inilah alasan di balik terbentuknya lembaga-lembaga
keuangan dan kerjasama regional baru yang tidak lain merupakan cara untuk
mendukung mekanisme pembiayaan tersebut. Bentuk kekuatan-kekuatan ekonomi ini
yang kemudian mengorganisir dirinya hari ini, misalnya dipelopori oleh Cina dan
AS. Kita dapat melihat bagaimana Cina dan satelit kekuatan ekonominya berkumpul
membentuk Asian Infrastructure and Investment Bank (AIIB)[24], sementara US mengumpulkan aliansinya ke
dalam satu payung bernama Trans Pacific Partnership (TPP). AIIB akan terdiri
dari 57 negara, sedangkan TPP untuk saat ini telah disepakati oleh 11 negara.
Seperti yang juga diketahui bersama bahwa Indonesia termasuk salah satu dari
negara-negara pendiri AIIB dan juga sedang mengajukan diri untuk terlibat di
dalam TPP.
Dua badan tersebut memiliki skenario yang sama. Yaitu
bertugas untuk memastikan mengalirnya uang pinjaman untuk pembangunan
infrastruktur di negara-negara koloni, dan juga menjadi “uang muka” untuk
paket-paket deregulasi domestik terkait kepemilikan lahan dan urusan sewa
menyewa dalam mata rantai global.
Paket deregulasi tidak hanya ditujukan ke negara-negara
target perdagangan tanah, tapi juga deregulasi domestik di negara-negara maju
dari mana investasi tersebut berasal sebagai cara melapangkan jalan investasi.
Semisal aturan yang melarang penggunaan dana jaminan sosial oleh negara untuk
digunakan dalam investasi dan regulasi yang melarang kepemilikan properti
(tanah) di luar teritori sebuah negara.
Sementara di negara-negara tujuan pasar, deregulasi tidak
hanya dipahami sekadar urusan administratif yang menyangkut persoalan pembebasan
tanah. Lebih jauh dari itu, negara-negara miskin dan berkembang diharuskan
untuk segera mendorong kebijakan upah buruh murah lengkap dengan sistem
perburuhan yang tidak adil. Tersedianya buruh murah adalah pelicin penting
dalam mengundang investasi luar negeri. Selain itu di sektor agraria,
negara-negara tujuan investasi diharuskan melakukan legalisasi tanah dalam
bentuk sertifikasi hak individu. Sertifikasi tanah sebagai milik perseorangan
tidak lain dimaksudkan sebagai tahapan menuju konsolidasi alat-alat produksi
agar semakin mudah diambil alih.[25] Itu mengapa, investor di bidang
pangan dan energi mendorong penuh semangat pendataan-pendataan wilayah komunal
untuk kemudian segera diberikan pengakuan hak milik individu. Kepemilikan tanah
secara kolektif dengan basis argumentasi mengenai tapal batas dan kepemilikan
yang dilandaskan pada sejarah atau sistem tenurial tradisional, dianggap
menghambat perluasan investasi di sektor pangan dan energi.
Untuk mendukung hal tersebut, melalui campur tangan
badan-badan pertanahan, negara menggalakkan kampanye agar setiap tanah yang
selama ini belum terdata segera dipetakan, didata sebelum kemudian
didistribusikan dalam pecahan-pecahan yang lebih kecil.[26]
Selain industri pangan dan energi yang merupakan
‘perampasan tanah dari luar’ (external land grabbing), negara-negara miskin dan
negara berkembang juga akan mendorong dirinya untuk melakukan ‘perampasan tanah
ke dalam’ (internal land grabbing). Jika ‘perampasan dari luar’ berarti tanah
akan digunakan sebagai alat tawar hutang dan oleh karenanya harus diagunkan ke
investor asing, dalam mekanisme ‘perampasan tanah ke dalam’ negara adalah aktor
yang akan melakukan perampasan tanah terhadap warganya. Tanah-tanah yang akan
dirampas ini kemudian akan dialihfungsikan untuk pembangunan infrastruktur
(mis. sarana transportasi) dan pengembangan jenis-jenis bisnis satelit seperti
properti dan waralaba.
Jika ‘perampasan tanah dari luar’ akan marak terjadi di
daerah-daerah pedesaan, maka ‘perampasan tanah ke dalam’ justru akan mengambil
lokasi di daerah perkotaa dan atau sub-urban. Kita menyebutnya, penggusuran.
Sebagai contoh, pembangunan jalur kereta api cepat
Jakarta-Bandung. Proyek yang disponsori Cina ini tidak hanya menyingkirkan
rakyat yang tanahnya diambil untuk pembangunan rel kereta api dan stasiun
antara.
Namun, mereka yang berada di sepanjang lintasan kereta
tersebut (terutama yang berlokasi di sekitar stasiun) secara otomatis menjadi
kelompok paling rentan dan sasaran tembak paling mudah dari pembebasan lahan
untuk bisnis properti dan waralaba. Dalam beberapa tahun ke depan, kita akan
menyaksikan tumbuhnya apartemen-apartemen yang disediakan bagi kelompok
berpendapatan menengah ke atas, dan toko-toko sejenis Alfa Mart, Indo Maret dan
7-11 akan bertebaran.
Kasus lain, seperti proyek reklamasi Teluk Jakarta yang
diperkirakan akan menelan biaya 400 trilyun rupiah. Selain menyingkirkan
kelompok nelayan dan mengganggu tatanan ekosistem pantai dan laut, reklamasi
ini ditujukan sebagai sarana pendukung investasi dengan menyediakan pusat
industri jasa dan lahan baru untuk berkembangnya bisnis properti. Kita bisa
menengok sejarah beberapa kasus reklamasi di Jakarta. Reklamasi pantai Pluit
sepanjang 400 meter di awal dekade 80-an kemudian menjadi pemukiman mewah
bernama Pantai Mutiara. Tahun 1981, sisi utara Ancol direklamasi untuk menjadi
pusat rekreasi bernama Taman Ancol. Tahun 1991, kawasan hutan bakau Kapuk
direklamasi dan akhirnya menjadi perumahan mewah Pantai Indah Kapuk. Tahun
1995, dilakukan kembali reklamasi untuk dijadikan zona industri yang disebut
Kawasan Berikat Marunda.[27]
Daftar tersebut harusnya dapat menjawab pertanyaan
mengapa reklamasi getol dilakukan. Setelah teluk Manado, lalu bergeser ke
selatan dengan menimbun pantai Losari di Makassar dan kini teluk Benoa.
Persoalan yang kemudian menggelitik adalah masih banyak
di antara kita yang tampak tidak mampu untuk melihat ikatan antar
persoalan-persoalan ini sebagai sebuah kesatuan. Paket upah buruh murah yang
diluncurkan Jokowi dipandang terpisah dengan deregulasi mekanisme pemberian
ijin alih fungsi hutan dan tata cara pembebasan lahan. Terbitnya rencana
ekonomi untuk membangun 24 pelabuhan yang akan mendukung tol laut, 15 bandara
baru untuk menggantikan bandara lama yang dianggap tidak layak,[28] rencana pembangunan 9 bandara kargo
baru, terbitnya rencana untuk membangun jalur kereta api di Kalimantan,
Sumatra, Papua dan Sulawesi serta berbagai penggusuran yang marak terjadi di
Jakarta dan kota-kota besar lain dalam beberapa tahun terakhir, mestinya harus
dilihat sebagai hal-hal yang terkait dan terikat dengan rencana investasi
perkebunan skala raksana untuk sumber energi dan pangan.
Kesadaran akan pentingnya melihat sebuah persoalan secara
totalitas inilah, yang mendesak dilakukan oleh seluruh gerakan progresif saat
ini. Jika kita terus terjebak dalam advokasi dan perjuangan berdasarkan pada
isu-isu tertentu yang terisolasi satu sama lain, sebagaimana yang kita lakukan
sepanjang15 tahun lebih pasca tumbangnya Soeharto, maka selama itu pula
advokasi dan perjuangan kita akan selalu berujung pada kebuntuan, untuk tidak
mengatakan kegagalan.
***
Penulis adalah Peneliti
di Yayasan PUSAKA: Pusat Studi, Advokasi dan Dokumentasi Hak-hak Masyarakat
Adat
___
[3] J. W. Seaquist, Emma Li Johansson, Kimberley Nicholas, Architecture
of the global land acquisition system: applying the tools of network science to
identify key vulnerabilities. (Lund University, November 2014)
[5] British Geological Survey, African Mineral Production, (BGS,
Juni 2009)
[6] Sara Nordbrand dan Petter Bolme, Powering the Mobile World:
Cobalt Production for Batteries in DR Kongo and Zambia, (Swed Watch, November
2007)
[9] Di tahun 2008, Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, mengumumkan
penyewaan sawah orang-orang Khmer kepada Qatar dan Kuwait. Tujuannya agar supaya
kedua negara tersebut dapat memproduksi beras mereka sendiri. Hun Sen memang
tidak menyebutkan berapa luas sawah yang akan dipinjamkan. Namun yang jelas,
industri agribisnis tergolong rakus dalam penguasaan tanah. Pada saat yang
bersamaan, Food and Agricultural Organization (FAO), mengucurkan bantuan
sebesar 35 milyar dolar untuk membantu bencana kelaparan yang menimpa desa-desa
di bagian selatan dan barat negeri itu.
[10] Ujjaini Halim (ed), Neoliberal Subversion of Agrarian Reform
2nd Edition, (I3D Foundation, 2014)
[12] Di tahun 2008, negara-negara Teluk mesti menanggung gelembung
inflasi atas impor bahan makanan yang membengkak dari 8 milyar USD hingga
menyentuh 20 milyar USD (kenaikan 150%). Ketika Merauke Integrated Rice Estate
(MIRE) pertama kali diluncurkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono di tahun 2006,
Bin Laden Group yang berasal dari kawasan ini telah menyanggupi untuk
pembiayaan investasi. Mereka kemudian menarik diri akibat krisis finansial yang
terjadi tahun 2008 karena melemahnya mata uang lokal di hadapan dolar Amerika.
[13] Di Uni Emirat Arab misalnya, 80% populasinya merupakan pekerja
migran yang datang dari Asia yang merupakan pemakan beras dan bukan gandum
(makanan utama di negeri tersebut).
[17] Biasa dikenal dengan nama COP (Conference of the Parties). COP
terakhir, untuk ke 21 kalinya diselenggarakan di akhir tahun 2015 kemarin di
Paris.
[18] Sime Darby Plantation, Palm Oil Facts and Figures in
Malaysia, (SDP, April 2014)
[19] Tuk Indonesia, Kuasa Taipan: Kelapa Sawit di
Indonesia, (TuK Indonesia, 2015)
[20] Amartya Sen, Poverty and Famine: An Essay Entitlement and
Deprivation, (Oxford, 1981)
[23] Ministry of National Development Planning/National Planning
Development Agency, “List of Medium-Term Planned External Loans
2015-2019”, (Bappenas, 2015)
[25] Kasus konsolidasi tanah ini misalnya terjadi di Cina dan India
dalam lima tahun terakhir. Negara mengambil inisiatif untuk melakukan
sertifikasi atas lahan-lahan kolektif untuk kemudian didistribusikan menjadi
kepemilikan individual. Tanah-tanah yang telah terdivisi atas nama perseorangan
ini kemudian dapat dengan mudah diambil alih karena melemahnya ikatan tenurial
yang dahulu eksis ketika pengelolaan dan pengakuan atas tanah didasarkan pada
komunalisme.
[26] Lembaga-lembaga pemetaan yang mayoritas adalah gerakan masyarakat
sipil (non-government organizations) banyak yang abai soal ini. Imajinasi
mengenai pengakuan negara dan dorongan agar tanah dapat segera didata dalam
bentuk apapun, luput melihat bahwa strategi perampasan tanah justru akan jauh
lebih mudah dilakukan ketika urusan jual-beli dibebankan kepada tiap-tiap
orang.
[28] Bandara-bandara lama ini kemudian diserahkan pengelolaannya
kepada TNI Angkatan Udara.